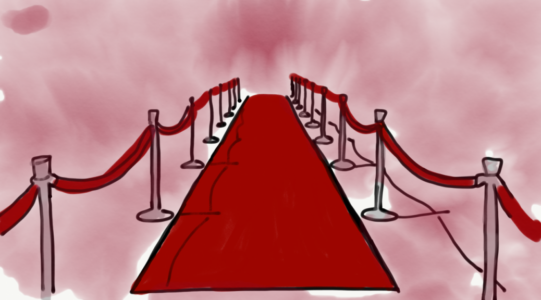Menjelang Idul Fitri tahun 2001, Presiden Gus Dur menerima laporan tentang persiapan Istana Merdeka untuk melaksanakan open house seperti tahun sebelumnya. Kali ini ada yang berbeda. Penulis buku Presiden Gus Dur: The Untold Story (2014), Priyo Sambada, menuturkan bagaimana protokol Istana merencanakan Presiden dan Ibu Negara akan menerima rakyat di teras Istana, tidak di Ruang Kredensial Istana Merdeka yang biasa digunakan untuk berbagai acara resmi Presiden seperti menerima kredensial duta besar negara sahabat, foto bersama tamu negara, dan acara formal lain.
Protokol Istana memberikan alasan bahwa ini dilakukan untuk menjaga karpet Istana yang belum lama diganti. Diperkirakan ribuan rakyat akan memanfaatkan momentum open house Lebaran untuk menginjakkan kakinya di Istana.
Ribuan rakyat berbaris dan bergerak dalam satu jalur tentu akan menciptakan alur jejak khas di karpet batu. Pendek kata, akan merusak karpet baru seharga miliaran rupiah tersebut. Bagi protokol Istana, kerusakan itu adalah sesuatu yang tak boleh terjadi. Harus diatur agar rakyat bisa dicegah dari karpet Istana yang mulia itu.
Mendengar alasan tersebut, Presiden Gus Dur pun sempat naik darah dan berkata, “Memangnya kenapa kalau rakyat merusak karpet ini? Ini dibeli dengan uang rakyat, karpet ini milik rakyat, hak mereka untuk menginjak karpet ini!”
Alhasil, dalam open house Idul Fitri tahun tersebut, rakyat tetap diterima di ruang paling terhormat di Istana Merdeka. Prediksi protokol Istana pun terbukti: di karpet baru tertinggal jejak menjalur dari ribuan pasang kaki rakyat yang ingin bersilaturahmi dengan pemimpinnya. Yang berbeda hanya pemaknaan dari jejak tersebut, yang merupakan buah dari sudut pandang mendasar dan keberpihakan. Pada rakyat atau pada elite penguasanya.
Bangsa kita agaknya masih belum sepenuhnya move on dari mental set feodalistik. Pemimpin dan elite politik masih sering dipandang sebagai penguasa negara dan bangsa dengan kewenangan penuh atas bumi dan segala isinya. Akibatnya, rakyat kehilangan daya kritis untuk menempatkan dirinya dalam perspektif dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Masih banyak warga yang dipandang dan memandang dirinya sendiri sebagai kelompok yang harus melayani pemimpin dan elite politik, bukan sebaliknya.
Sebagai contoh, mental set feodalistik ini juga berdampak pada bagaimana rakyat memandang korupsi. Pajak tidak dimaknai sebagai harta kolektik rakyat yang bergoyong royong membangun negara untuk bangsa, tetapi tetap dicerna sebagai upeti kepada penguasa.
Layaknya di masa feodal, upeti itu sepenuhnya menjadi milik penguasa untuk digunakan sesuai kebijakan sang penguasa. Jika beruntung mendapat penguasa yang arif, harta penguasa akan digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya. Jika apes mendapat penguasa yang lalim, rakyat tak dapat berbuat apa-apa. Maka, walaupun jajak pendapat pembaca Kompas tahun 2019 menunjukkan korupsi sebagai hal yang dianggap paling menghambat kemajuan Indonesia, rakyat tak mampu berbuat banyak.
Mental set ini pula yang membuat bangsa kita masih memberikan ruang keutamaan kepada penguasa dan elite politik, juga kepada pemilik modal yang mampu memengaruhi kebijakan negara dengan kuasa kapital dan kerap menempatkan rakyat yang lemah pada posisi rentan. Sebuah tulisan di media sosial memotretnya sesederhana ini: dalam kondisi pandemi dan keterbatasan ventilator dan ruang isolasi, akankah para pejabat dan keluarganya diutamakan dari rakyat biasa sebagaimana selama ini terjadi dalam berbagai konteks lainnya?
Sadar ataupun tidak, “karpet-karpet” negara di berbagai sudut Indonesia lebih banyak digunakan untuk menyambut para petinggi dan elite politik serta elite ekonomi bangsa ini sebagaimana karpet Istana kala itu. Dan Gus Dur bersikeras melawannya.
Sikap Gus Dur konsisten dengan keyakinan dan inti perjuangannya sejak tahun 1970-an, yaitu kedaulatan rakyat. Ia meletakkan rakyat sebagai pemilik sejati bangsa dan negara ini dengan segenap hak dan kewajibannya sehingga segalanya harus dikembalikan pada kepentingan rakyat belaka. Ini selaras dengan sumber keyakinan yang sering dikutipnya, yaitu kaidah tasharruf al-iman ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahat (kebijakan seorang pemimpin untuk rakyatnya harus disandarkan pada kemaslahatan rakyat).
Cara pandang ini membuat karpet Lebaran di Istana dimaknai sebagai hak rakyat, bukan hak pemimpin. Sang karpet tidak dianggap sebagai milik penguasa yang berasal dari persembahan rakyat, tetapi dihargai sebagai milik rakyat. Pemimpin berkewajiban untuk menggunakannya untuk kemaslahatan bersama.
Bagi seorang pejuang demokrasi sejati, karpet tersebut bukan hanya untuk menyambut para elite politik dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Karpet itu juga bukan hanya untuk pemilik modal yang dieluk-elukan sebagai penggerak ekonomi negara, melupakan bukti sejarah kontribusi dan ketangguhan rakyat di sektor ekonomi informal. Dan karpet itu bukan hanya untuk para pemuka agama yang dibutuhkan dukungan politiknya untuk memenangi hati umat.
Wujud keberpihakan harus berupa kebijakan yang rumit. Ia bisa tampak dalam gestur dan tindakan yang sangat mendasar: karpet milik rakyat digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk menjaganya tetap bersih dan indah.
Artikel ini pernah dimuat di rubrik “Udar Rasa” Kompas, 31 Mei 2020