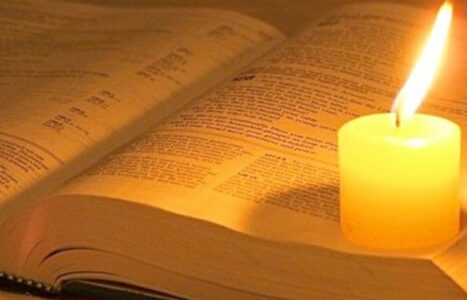Semester ini saya mengajar dua matakuliah: religious pluralism dan religious freedom. Yang pertama itu matakuliah baru, dan jika ada waktu saya ringkaskan diskusinya tiap akhir pekan, walaupun tidak mungkin memotret dinamika yang terjadi di kelas.
Minggu pertama ini kita mendiskusikan pandangan Alkitab tentang agama-agama, dengan membaca Injil Matius dan 1 Korintus. Saya mengawali dengan pertanyaan: What is Christianity’s relationship to other religions? What can we find of value in other religions?
Dua hal diamati mahasiswa. Pertama, dari dua bacaan/teks itu, segera terlihat betapa sedikitnya ayat-ayat Alkitab yang berbicara atau memberikan petunjuk bagaimana seharusnya umat Kristiani menyikapi agama-agama lain. Namun, dari bahan yang tersedia dapat diidentifikasi beberapa “arahan”.
Kedua, dari beberapa ayat yang relevan, arahan Alkitab tampak tidak tunggal. Dengan kata lain, ada beragam perspektif terkait “value” dan peran agama-agama lain dalam Alkitab. Jadi, terdapat ambivalensi atau “tension” dalam menilai keberadaan agama-agama lain, terutama soal konsep keselamatan.
Di kelas ini ada dua Romo (priest) yang ikut belajar. Semua mahasiswa saya beragama Kristen, sebagian besar Katolik. Jadi, mereka sangat familiar dengan Alkitab. Saya mengajukan pertanyaan polling: Apakah secara umum pandangan Alkitab tentang agama lain bersifat positif atau negatif?
Setelah berdiskusi soal istilah “positif” dan “negatif”, 100% mahasiswa berpendapat pandangan Alkitab relatif “negatif”. Dalam Hebrew Bible/Perjanjian Lama, mereka yang tidak mengimani Yahweh divonis “musyrik” atau “tidak bertuhan.” Seorang mahasiswa memberikan contoh ayat-ayat dari Book of Wisdom.
Saya mengarahkan diskusi untuk memfokuskan pada soal “keselamatan penganut agama non-Kristen” dalam Injil Matius dan 1 Korintus. Kesarjanaan modern tentang Injil Matius dan 1-2 Korintus sangat luas, saya memperkenalkan sedikit, tapi tidak menjadi fokus utama. Saya lebih tertarik mendiskusikan perspektif mahasiswa.
Dua poin yang diangkat mahasiswa menarik perhatian saya. Pertama, aspek menonjol dalam dua teks/bacaan kita ialah bahwa keselamatan hanya bisa dicapai melalui Yesus. Dalam Matius 1:23, Yesus diidentifikasi sebagai yang diramalkan oleh Isaiah, yakni “Immanuel” (Tuhan bersama kami).
Dalam Korintus, Paulus menyebut Yesus “the power of God” bagi keselamatan, dan “the Lord of glory”. Itu semua mengesankan pesan eksklusivitas, namun perlu diingat, pesan kasih (love) sangat dominan dalam ajaran Yesus, seperti digambarkan Matius. Konsep “kasih” ini bisa dimaknai universal.
Dalam khutbah di atas bukit, Yesus mengajarkan bahkan untuk mengasihi musuh-musuh yang mempersekusi kita. Artinya, kasih Tuhan menyelimuti semua, termasuk para pengikut agama lain. Ini pembacaan yang cukup inklusif.
Namun demikian, mahasiswa segera mengamati bahwa “kasih” tidak boleh dipahami dengan mengabaikan kebenaran (truth). Paulus menulis, “Love does not rejoice at wrongdoing, but finds its joy in the truth” (1 Korintus, 13:6). Well, kalau begitu, konsep “kasih” tidak seinklusif yang umum dipahami.
Tensions semacam ini lebih jelas lagi bila bicara soal keselamatan. Ini poin kedua yang menyita perhatian kelas. Matius 25 menggambarkan suasana Hari Akhir ketika Yesus mengadili nasib manusia menjadi ahli surga (kelompok kanan) atau neraka (kelompok kiri). Kriterianya adalah perbuatan baik, bukan keimanan eksklusif.
Untuk lebih detailnya, baca Matius 25, terutama ayat 35 dan 36. Membaca ayat itu mengingatkan saya pada al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 62 atau al-Ma’idah (5) ayat 69. Kriteria keselamatan adalah iman kepada Allah dan perbuatan baik, apapun agama yang dipeluknya.
Namun, banyak ayat lain dalam Matius menempatkan Yesus dalam posisi unik bagi keselamatan. Tak ada jalan lain, kecuali melaluinya. Coba baca pasal-pasal berikut: 3, 16, 17 dan 28. Akan segera muncul kesan teologi eksklusif. Ayat-ayat tersebut menjadi landasan kerja-kerja misionaris.
Ambivalensi serupa dalam dijumpai dalam 1 Korintus, yang tak perlu saya tuliskan di sini. Aspek lain yang menyita perhatian mahasiswa (maksud saya: mahasiswi) saya ialah soal intonasi Yesus dalam khutbah di atas bukit terkait perceraian, Matius 5:31-32. (Saya bayangkan kaum feminis tidak suka ayat ini)
Pertanyaan mahasiswi saya: Why does this passage seem to specifically place the sin on the wife? Is the sin not just as bad for both parties? If this is the case, and the sin is, in fact, just as bad for both parties, why is the passage worded in this funny way? Maksudnya, kenapa sih perempuan selalu disalahkan?
Tentu, saya tidak bisa menjawab hanya dengan senyuman. Saya juga tak bisa hanya bilang: Biasa teks-teks kuno (ancient texts) memang cenderung bersikap begitu terhadap kaum perempuan. Bisakah anda bantu menjawab? Saya akan sangat mengapresiasi penjelasan anda.
Minggu depan kita akan diskusikan pluralisme agama dalam al-Qur’an dengan membaca al-Qur’an surat al-Ma’idah. Stay tuned. Maturnuwun…
Sumber: Facebook Mun’im Sirry