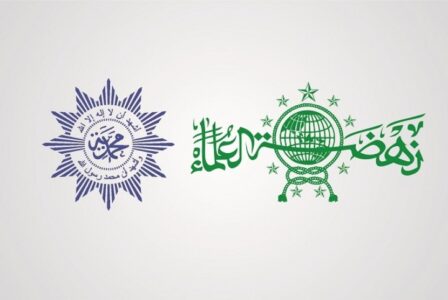Setiap kali datangnya bulan suci Ramadan, kita di Indonesia dapat merasakan perbedaannya. Teman saya pun demikian. Ia yang terlahir dari keluarga berlatar Muhammadiyah sehingga membuatnya mengikuti keluarganya tanpa mempertanyakan sebabnya. Namun, teman saya mengakui dirinya yang paling toleran terhadap perbedaan dua kutub organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.
Kala itu saya dan teman mengobrol santai mengenai perbedaan penetapan 1 Ramadan yang menjadi masalah lumrah di Indonesia. Setiap menghadapi bulan suci itu, masyarakat yang tidak terafiliasi di salah satu organisasi atau hanya sekedar mendengarkan organisasi itu jadi kebingungan. Mana yang harus mereka ikuti.
“Saya pernah menceritakan kepada kerabat saya bahwa, saya ikut pemerintah dalam penetapan 1 Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri. Mereka mengatakan bahwa, lebih baik saya masuk agama Kristen, daripada mengikuti penetapan tersebut.”
Pemerintah Indonesia sejak dulu dalam menentukan 1 Ramadan, setiap tahunnya dengan mengikuti Rukyatul Khilal atau hasil pengamatan dan musyawarah dari para ahli falakiyah Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga kerabat dari teman saya menganggap bahwa, mengikuti pemerintah sama dengan mengikuti ulama NU. Cerita ini sangat biasa bagi kebanyakan orang. Namun yang paling ekstrim adalah perkataan yang mengarahkan kepada kemurtadan. Perbedaan di sini dianggap hal yang haram.
Ditarik dari akar sejarahnya, fanatisme keagamaan ini memuncak pada masa Orde Baru runtuh (1965-1998). Heryanto (2015) merajut korelasinya dengan budaya populer. Di mana, gerakan politik Islam, gerakan pos-islamisme merebak dengan beredarnya film-film bernuansa islami seperti Ayat-ayat Cinta dan Wanita Berkalung Sorban.
Kedua representasi film yang disebutkan dalam tulisan Heryanto ini menjadi tonggak masyarakat Indonesia pada dekade pasca Orde Baru menunjukan politik identitas sebagai golongan agamawan. Gus Dur sendiri sering kali mengajarkan contoh-contoh melalui saluran film. Seperti yang pernah disebutkan beliau dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Beliau mengutip film The Singer not The Song yang menceritakan tentang seorang pastor yang bertugas di salah satu kota di Meksiko. Dan di akhir cerita itu berkesimpulan bahwa, sering kali kita menilai yang salah adalah song-nya atau lagunya. Dalam hal ini jika ditarik ke ranah agama, yaitu agamanya. Tapi yang sering luput adalah kita tidak melihat bahwa, yang keliru adalah singer-nya atau ‘sang penyanyi’. Dalam hal ini penganut agamanya—bisa juga kita sebut ‘oknum’.
Fanatisme perbedaan mazhab antara NU dan Muhammadiyah ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Sebab kedua kutub organisasi besar ini memiliki akar yang sama. Seperti yang dituliskan oleh Mochammad Ali Shodiqin dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah itu NU: Dokumen Fiqih yang Terlupakan.
Dalam tulisan itu, Shodiqin mencoba mengungkapkan temuannya terhadap dokumen fiqih Kitab Muhammadiyah 1924, yang aslinya ditulis dengan bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon. “Kitab itu (Fiqih Muhammadiyah 1924) juga kitabnya NU. Isinya sama dengan kitab-kitab pesantren yang banyak diajarkan dalam dunia NU,” tulis Shodiqin. Namun, NU belakangan lahir ketimbang Muhammadiyah. Tapi walaupun belum lahir, ulama-ulama pesantren yang kemudian mendirikan NU tiap harinya mengamalkan ajaran fiqih yang ada dalam kitab Fiqih Muhammadiyah 1924.
Mengutip NU Online (2014), Muhammad Zidni Nafi’ meresensi tulisan Shodiqin dan mengutarakan, di dalam buku ini dijelaskan bahwa setelah meninggalnya Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah pada 1912, generasi Muhammadiyah pada beberapa masa selanjutnya tercampur dengan paham Wahabi imbas dari kebijakan pemerintah Ibnu Saud di negeri Arab pada masa itu. Pada 1926 NU lahir dalam rangka merespons pemerintahan yang membawa paham Wahabi itu.
“Metamorfosis Muhammadiyah setidaknya dapat dibagi menjadi empat masa, yaitu Masa Syafi’i tahun 1912-1925; masa pembauran Syafi’i-Wahabi tahun 1925-1967; masa Himpunan Putusan Tarjih (HPT) tahun 1967-1995; dan masa pembauran HPT-Globalisasi tahun 1995 hingga kini,” tulis Nafi’ (nu.or.id, 2014).
Pada intinya buku tersebut, sebut Nafi’, bertujuan untuk memadamkan api yang selama ini membakar jarak antara Muhammadiyah dan NU. Harapannya masing-masing dapat memahami untuk melahirkan persatuan yang lebih erat bagi bangsa Indonesia.
Kembali pada kasus teman saya tadi. Setelah menceritakan hal yang dialami tersebut kepada saya, ia lantas tidak menyalahkan siapa pun. Sebab menurutnya beberapa generasi terdahulu masih merasakan romantisme jurang perbedaan antara NU dan Muhammadiyah.
Saya sendiri salut dengannya. Meski lahir dan besar pada lingkungan yang berpandangan cukup keras tapi tidak membuat dirinya ikut keras. Malah, ia mendaku sebagai salah satu kerabat dalam keluarganya yang toleran adalah dirinya sendiri.
Mazhab pada dasarnya menjadi pedoman kita dalam melaksanakan ibadah. Sebab umur kita terlampau jauh dengan Nabi Muhammad Saw. dalam mengikutinya secara tepat dalam beribadah. Bahkan pada masa Rasulullah masih hidup pun masalah perbedaan-perbedaan tetap terjadi. Dan para sahabat mengembalikannya masalah itu kepada Nabi dengan harapan perbedaan yang menyebabkan perpecahan tersebut segera mereda.
Seperti kasus yang membuat perpecahan antara kaum Anshar dan Muhajirin pada masa hijrahnya Nabi ke Madinah. Kedua kaum ini mengaku paling tepat untuk mengurusi keperluan Nabi, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Keduanya merasa benar sebab kaum Muhajirin yang notabenenya kerabat Nabi dari jazirah Arab berhak untuk mengurusinya. Sedang kaum Anshar berpendapat bahwa, Muhajirin yang kala itu terdiri dari kaum Quraisy notabene menolak ajaran beliau, sedang kaum Anshar—merasa berhak mengurusi keperluan Nabi—sebab mereka menerima ajaran Nabi tanpa syarat. Gus Dur sendiri paling getol dalam menyadarkan kepada masyarakat tentang perbedaan yang merupakan fitrah bagi bangsa ini. Perbedaan itu adalah rahmat bagi bangsa ini. Maka sudah benar yang diutarakan teman saya ketika kami akan berpisah setelah mengobrol. “Perbedaan mazhab itu bukanlah perbedaan agama.”