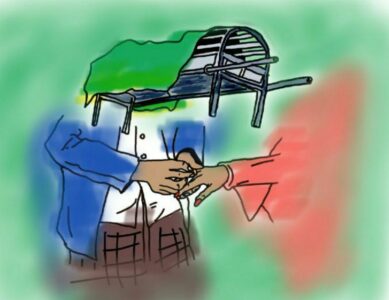Aku sedang mencuci gelas dan lepek saat seorang pemuda bertubuh tegap datang bersicepat. Rambutnya klimis, namun acak-acakan. Dari belakang kuperhatikan betul wajahnya namun aku tak mengenalinya. Ia sempoyongan masuk ke warungku tanpa mematikan sepedanya. Napasnya terengah-engah.
“Bisa bertemu dengan Abah Fadhol, Kang?” kata pemuda klimis itu kepada Narsun, pelanggan terakhirku malam ini, memecah keheningan warungku yang hendak tutup.
Namun Narsun tak langsung menjawabnya. Tampak ia cuma mengernyitkan dahi, dan menatap asing pemuda itu. Barangkali ia tak habis pikir malam-malam begini kok ada orang mencari Bapak. Sambil menyerbeti gelas, aku cekikikan melihat ekspresinya.
“Sebentar-sebentar duduk sini, Mas. Santai dulu. Sampean siapa? Kenapa? Malam-malam begini kok seperti keranjingan,” kata Narsun, tenang, seakan sudah akrab dengannya.
“Maaf, saya butuh cepat, Kang. Minta tolong ke Abah Fadhol sekarang. Bisa kan? Saya Niko,” kata pemuda itu tanpa jeda.
“Oh, Niko. Kalau cari Mbah Fadhol ya itu ke dalam. Tapi dengar-dengar beliau barusan sakit. Temui saja itu anaknya. Minum ini, kopiku masih ada. Kopi yang membuatmu makin cakep. Saya mau pulang dulu.”
Aku menghampirinya, meninggalkan cucian yang baru saja rampung. “Jangan pulang dulu, Sun,” kataku. Narsun patuh dan Niko cepat-cepat menatapku. Matanya berkedip cepat. Malam semakin senyap dan tinggal kami bertiga di tengah kesenyapan itu.
“Ada perlu apa dengan bapak saya? Memang beliau baru saja sakit. Mau apa, to? Nanti saya tanyakan. Sekarang bapak saya mungkin masih tid…”
“Kalau sekarang dibangunkan bisa, Kang?” Niko memotong ucapanku. Kami tak saling kenal namun caranya berkomunikasi sungguh di luar layaknya orang yang tak saling mengenal. Tak ada sungkan. Aku menelan ludah dan cuma diam.
“Saya minta dinikahkan, Kang. Jenazah mama saya sudah menunggu.” Niko menatapku penuh iba. Dari caranya menatap, di tengah malam seperti ini, aku kira permohonan itu tak dibuat-buat. Sementara Narsun terkejut, seperti menyesal sempat mengguraukannya.
Tanpa berlama-lama, kusuruh ia menunggu dengan Narsun, dan aku masuk rumah. Tiba-tiba naluriku bertekad membantunya. Paling tidak dengan memohon baik-baik kepada Bapak agar mau menikahkannya, meski ia telah pensiun dari penghulu. Aku kira jam segini malam memang sulit mencari penghulu desa.
Namun saat mendapati pintu kamar Bapak masih rapat tertutup, aku menjadi gamang. Aku tak lebih dari menyentuh pintunya. Aku teringat Bapak baru sembuh sehingga butuh istirahat yang cukup. Tapi aku juga tak kuasa menolak permohonan Niko.
Lalu aku putuskan kembali dan begini yang kukatakan kepadanya:
“Niko, sekarang kembalilah dulu, persiapkan semua keperluan acara. Bapak akan saya antarkan ke rumahmu nanti subuh. Begitu ya? Semoga lancar, dan mamamu mendapat tempat yang terbaik.”
Dan Niko segera pulang setelah mengucapkan lirih terima kasih. Sampai ia hilang, sementara Narsun terbengong, aku masih tak yakin betul apakah nanti Bapak berkenan. Aku malah khawatir Bapak tak cukup kuat untuk keluar rumah. Kalaupun bisa, jangan-jangan Bapak diam-diam nanti sudah ada acara pernikahan lain. Tapi ini bulan Sura. Kukira Bapak tak punya agenda.
Di luar itu aku sudah mempertimbangkan rencana paling konyol: bersiap-siap menggantikan Bapak. Semalaman, aku mencoba mengingat-ingat apa yang Bapak ucapkan dan bagaimana Bapak saat menikahkan. Mataku tak bisa terpejam.
***
Jalanan subuh sungguh lengang. Mobil Narsun melaju kencang. Dari belakang kemudi, Narsun bercerita bahwa Niko nanti menikah dengan wanita bernama Ningsih. Katanya, keduanya belum lama dekat. Namun mama Niko mendesaknya agar segera menikah. Nikolah satu-satunya tumpuan agar mamanya bisa memiliki cucu. Niko pun memenuhinya, setelah berkali-kali menunda.
“Itu kapan rencana aslinya?” aku menyela.
“Tak tau juga. Tadi malam ia tak bercerita kapannya. Keluarga si wanita yang menentukan harinya. Niko siap untuk kapan saja.”
Namun, di tengah persiapan itu, mama Niko meninggal dunia. Sesak napasnya kumat dan tak tertolong sebelum sempat dirawat di rumah sakit. Niko merasa meyesal mengapa ia terus menunda pernikahannya. Karena itulah, ia meminta akad pernikahan dilangsungkan sekarang juga. Katanya, kalau mamanya tidak bisa melihatnya menikah, paling tidak tubuh mamanya masih ada di sampingnya.
Di jok belakang, aku mendengarnya dengan saksama. Mataku perih. Dan di depan sana, Bapak kerap menguap, juga sesekali terbatuk-batuk.
***
Niko sudah duduk bersimpuh di hadapan meja kecil yang dilapisi kain putih tipis berenda. Rambutnya masih klimis. Raut mukanya tegang dan terlihat siap. Ia tampak mencoba sekuat tenaga menahan tangisnya; sesenggukan tak bersuara. Seseorang lelaki di sampingnya, kukira pamannya, tak henti-henti menenangkannya.
Yang tak kalah tegang adalah Ningsih yang duduk di belakangnya. Ia mengenakan pakaian jubah panjang berwarna hijau gelap. Tak ada gaun yang mengilap. Kantong matanya menebal, seperti baru terhantam benda keras. Berhelai-helai tisu tercampak di sampingnya. Sedangkan di seberang meja berenda itu, jasad terbujur kaku, dibalut kain kafan, dan tak bernapas di atas keranda kayu yang terbuka. Itulah mama Niko.
Tak ada kuade atau hiasan apa-apa di ruang tamu yang luas itu, selain kembang melati, krisan, anyelir, gladiol bercampur aduk dengan air yang mungkin nantinya disiramkan di atas tanah kuburan. Wanginya menyeruak ke penjuru ruangan. Aku rasa acara ini lebih ke aroma kematian daripada pernikahan.
Hari masih begitu pagi, udara dingin, tapi telah banyak orang yang tiba. Entah untuk bertakziah atau menyaksikan akad nikah. Atau mungkin kedua-duanya. Yang jelas mereka semua menunduk dalam-dalam, seakan tak kuat menahan duka Niko. Tak ada perbincangan, selain sesekali tangis sesenggukan. Suasana begitu dingin, senyap, dan menyayat.
Bapak masih pergi ke kamar mandi, bersiap-siap dan mengambil wudhu. Sepertinya ia butuh sedikit kesegaran setelah perjalanan. Tadinya, beliau tak jadi ikut karena merasa belum enak badan, kalau saja aku tak meminta Narsun untuk membujuk rayu. Demikianlah aku selalu percaya dengan kemampuan komunikasi Narsun.
Sekarang tinggal menunggu Bapak dan akad nikah langsung dimulai. Sesekali Niko menatapku. Aku paham. Lalu Niko berkata lirih, bahwa penggali kubur sudah menunggu dan liang lahad sudah selesai. Aku beranjak menjemput Bapak di belakang.
Sementara itu, Narsun kutinggalkan sendirian duduk-duduk di pojok ruangan, tepat di samping kipas angin seraya menikmati kopi panas yang dihidangkan, serta beberapa kudapan. Matanya liar ke sana kemari. Aku tau ia memiliki pengamatan yang cemerlang.
Beruntung, Bapak juga telah selesai. Kukatakan padanya jika kedua mempelai sudah siap. Ia mengangguk pasti, sambil merapikan songkok hitamnya.
Baru saja kembali ke ruangan bersama Bapak, aku mendapati wanita berusia lima puluhan duduk di seberang meja berenda itu, tempat yang seharusnya diduduki Bapak.
“Begini Bu Ajeng, tak ada yang menghendaki ini. Niko pun tak ingin rencana semulanya gagal. Tapi mamanya ini, Bu, mamanya! Keadaan berkata lain. Lihat, Bu. Tolonglah! Semua sudah siap. Memang mau mundur sampai kapan?” kata orang yang kukira paman itu, tegas dan mengentak, seraya membelai pundak Niko. Sepertinya suasana mendadak tegang.
“Sampai hari yang dulu telah kami tentukan,” jawab wanita yang dipanggil Bu Ajeng itu sambil merunduk. Di belakangnya, Ningsih menarik-narik bajunya dengan penuh tangisan.
“Itu kalau normal. Kalau ini siapa kira, Bu? Kakak saya sejak lama ingin sekali melihat anaknya menikah. Ningsih juga tau itu.”
Bu Ajeng menatap Ningsih, seperti meminta konfirmasi. Namun Ningsih hanya bisa terisak dan sama sekali tak kuasa mengangkat wajahnya.
Aku menjadi bimbang. Aku tahan Bapak untuk tak masuk ke ruang tamu terlebih dahulu. Beliau sudah tua dan tak perlu terlibat dalam perdebatan yang barangkali mendebarkan jantungnya, apalagi perkara orang lain. Beliau kuminta duduk-duduk di ruang tengah. Kuambilkan kopi untuknya. Meski tampak tenang, aku tetap saja merasa sungkan padanya. Narsun juga tampak masih berada di tempat yang sama, nun di sana.
“Tapi di alam lain bukankah beliau justru makin leluasa? Aku yakin beliau makin jelas melihat apa yang kita lakukan,” Bu Ajeng seperti tak mau mengalah.
Tak ada yang menanggapinya. Beberapa orang yang tadinya di luar turut masuk ke rumah. Ruangan makin sesak. Batuk-batuk Bapak sesekali aku dengar.
“Sudahlah, Bu Ajeng. Mari, Ningsih. Mari kita mulai.”
“Tapi ini bulan Sura, Pak. Semua orang juga tau bagaimana …” seru Bu Ajeng sambil mengarahkan tangannya ke para tamu.
Orang-orang mengangkat wajahnya, seakan tersentak. Beberapa bahkan langsung berdiri. Semua mata menyoroti Bu Ajeng. Ningsih tak berhenti menangis. Suasana seolah menjadi serba salah. Keheningan semakin terasa menyayat. Paman hanya menunduk dan tak menjawabnya. Tapi Niko mendadak menegak.
“Lalu bagaimana? Apa saya harus menunggu bulan depan … Sampai mayat mama membusuk?” ucap Niko tiba-tiba, menyeruak cepat. Mengagetkan. Seperti guntur yang menggelegar di tengah badai. Napasnya berat. Aku kira itu pertanyaan yang tak butuh jawaban; pertanyaan yang sebetulnya tak pantas dikatakan di depan mayat ibunya. Tapi kemarahan sepertinya membuat ia hilang kesadaran.
“Sudah, nak, sudah … “ terdengar suara meronta-ronta dari belakang. Namun Niko seperti tak peduli. Matanya semerah saga.
Ruangan menjadi senyap. Tak ada yang menimpalinya. Beberapa orang malah makin keras tangisannya.
Di tengah keheningan itu, dari samping, Narsun tiba-tiba merangsek berjalan ke tengah, ke arah meja itu. Entah apa yang hendak ia lakukan. Aku hendak mencegah. Tapi tanganku terlampau jauh. Narsun berdiri di samping meja berenda. Mukanya penuh keyakinan. Orang-orang terheran-heran melihatnya.
“Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Mas Niko, Mbak Ningsih. Cukup. Sebentar jangan diteruskan. Cukup,” Narsun berhenti. Tatapannya berkeliling.
“…Tolong dipikir dulu. Ini mau sampai kapan?” ia menggantung pertanyannya.
“Apa kalian tak kasihan pada penghulunya? Itu Abah Fadhol sudah di dalam…” kata Narsun sambil menudingkan tangannya ke pintu masuk ruang tengah, diikuti tatapan orang-orang.
“Beliau ini sudah tua. Beliau enggak tau apa yang kalian omongkan. Subuh-subuh sudah rela datang ke sini, beliau abaikan sakit-sakitnya. Katanya disuruh menikahkan. Tapi di sini cuma nonton debat-debat. Masa enggak kasihan? Ya, gimana ya. Hormati orang-orang tua seperti Abah Fadhol dululah, sebelum jauh-jauh ngomong bulan Sura.”
Aku kaget, namun tak heran dengan keberaniannya. Narsun berhenti, orang-orang diam dan sejenak menghentikan tangisnya.
Narsun memberi isyarat padaku. Ia seolah tau keresahanku. Aku tuntun perlahan Bapak ke dekatnya, di samping meja. Selintas aku melihat jenazah itu. Aku bergidik. Sejenak aku tak tau lagi bagaimana Niko, Ningsih, atau Bu Ajeng. Yang aku tau, aku bersyukur dan merasa benar tadinya tak jadi menghalangi Narsun saat merangsek ke tengah.