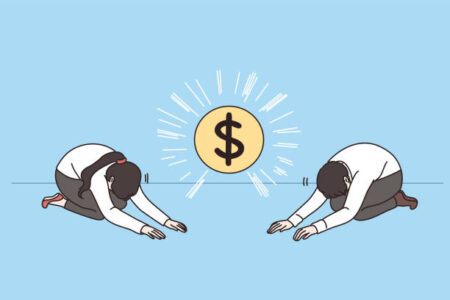Sejak kasus Mario Dandy yang menyeret ayahnya Rafael Alun, gaya hidup mewah para pejabat dan pesohor di Indonesia menjadi perhatian publik. Apalagi dengan terungkapnya kasus korupsi timah yang melibatkan Helena Lim dan Harvey Moeis, yang kerap mempertontonkan gaya hidup mewahnya melalui platform media sosial.
Di kanal Youtube atas nama Aini, saya menemukan sebuah esai video bertajuk East Asia is Obsessed with Luxury (and Gen Z Pay the Price). Ia membahas bagaimana di Asia Timur (dan Asia umumnya) terjadi kenaikan penjualan barang-barang jenama mewah, terutama di Jepang, Korea Selatan, dan China. Bahkan sebuah model tas keluaran jenama tersohor disebut sebagai ”3 Second Bag”, saking mudahnya menemukan orang membawa benda seharga puluhan juta rupiah tersebut.
Menurut Aini, terdapat perbedaan mencolok pada kultur orang Asia dan orang Barat (baca: Amerika dan Eropa) dalam konsumerisme. Dalam kultur Barat, seseorang membeli barang jenama mewah untuk (kepuasan) diri sendiri. Sebaliknya, dalam kultur Timur, seseorang membeli barang jenama mewah lebih banyak untuk mendapatkan pandangan positif dari orang lain.
Nilai-nilai budaya membawa pengaruh besar dalam hal ini, tidak melulu tentang kesenangan terhadap benda-benda mewah. Nilai konformitas, peran sosial, face culture, dan hierarki sosial menjadi faktor penentu obsesi terhadap benda-benda jenama tersohor.
Aini menjabarkan face culture sebagai kultur di mana wajah/muka atau penampilan menjadi simbol utama martabat seseorang dan penentu respek dari sekitar. Istilah ini terlihat dalam berbagai ekspresi seperti kehilangan muka atau tidak punya muka. Sebagai turunannya, masyarakat komunal menganggap penampilan sebagai tolok ukur martabat individu. Seseorang yang tampak glamor dengan benda-benda mewah dipersepsi sebagai seorang dengan martabat atau gengsi yang lebih tinggi.
Dalam konteks peran sosial, gaya hidup penuh kemewahan ini dipengaruhi oleh nilai independensi individu versus nilai peran sosial. Dalam kultur Barat, setiap individu memiliki independensi atas dirinya. Contohnya, apabila ia menjadi orang sukses, ia menjadi satu-satunya penerima manfaat dari kesuksesannya. Tidak ada orang lain yang akan mendapatkan atribusi otomatis dari kesuksesan tersebut, walaupun itu saudara sekandungnya.
Sebaliknya dalam kultur Asia yang bercorak kolektivisme, setiap individu adalah bagian dari kelompoknya. Apabila seseorang menjadi orang sukses dalam standar kultural, penerima manfaatnya meluas. Privilese secara otomatis menggelombang kepada orang-orang di sekitarnya.
Di Indonesia, kita mudah melihatnya dalam praktik sehari-hari keluarga petinggi dan pesohor. Berbagai kemudahan dan fasilitas diterima pasangan, anak-anak, keluarga mereka dan lingkaran terdekat, sebagai efek riak (ripple effect). Contoh mutakhir adalah skandal biaya ojek makanan dan tiket pesawat anak cucu Syahrul Yasin Limpo yang ditanggung oleh anggaran Kementerian Pertanian.
Di sini, gaya hidup mewah pun muncul sebagai dampak kesuksesan sang pesohor atau pejabat. Semakin sukses sang pesohor, semakin mudah melihat perubahan pada lingkungan terdekatnya.
Dalam masyarakat individualis, orang membeli barang mewah karena ia suka dan menikmati barang tersebut. Dalam masyarakat komunal, orang membeli barang mewah karena ia memiliki kebutuhan untuk mempertahankan martabatnya, bahkan walaupun ia tidak benar-benar menyukai barang tersebut.
Seorang Perencana Keuangan menyebut ini sebagai budaya membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang tidak dimiliki (alias kredit!) hanya demi mempertahankan gengsi di hadapan orang yang kadang tidak disukai. Sayangnya, ini bukan hanya persoalan personal, melainkan dapat menimbulkan persoalan sosial.
Fenomena ini pernah diangkat oleh BTS, grup fenomenal asal Korea Selatan yang banyak menyampaikan kritik sosial dalam lagu-lagunya, termasuk tentang sistem pendidikan, kesenjangan sosial, kapitalisme dan korupsi di negaranya.
Dalam lagu ”Spine Breaker”, BTS menyoroti fenomena para remaja Korea Selatan yang terjebak tren jaket North Face. Kala itu, para siswa SMA menganggap jaket yang tidak murah ini menjadi ukuran gengsi dan kelas sosial. Siswa yang tidak memakainya menjadi paria, dan siswa yang menggunakan model termahal menjadi crème de la crème. Karenanya, para remaja ini memaksa orangtua mereka untuk membelikan jaket tersebut.
Tuntutan ini menjadi spine breaker atau mematahkan tulang punggung orang-orang tua yang harus bekerja keras untuk memenuhinya. Berhenti bersikap kekanak-kanakan, kalian tidak akan membeku kedinginan walaupun tanpa jaket itu, semprot BTS dalam lagu tersebut.
Tren semacam ini terjadi dalam berbagai bentuknya di berbagai kelompok masyarakat, dan menunjukkan bagaimana hierarki dan konformitas sosial berbalik menjadi racun dalam kehidupan pribadi maupun kelompok. Gaya hidup mewah bukan lagi sekadar selera dan kesukaan, melainkan menjadi kebutuhan karena ia menentukan gengsi dan posisi dalam hierarki sosial.
Di China, 18 persen gen Z membelanjakan pendapatannya untuk barang mewah, jauh melebihi angka 3 persen di kelompok usia produktif lainnya. Sebagai respons, Pemerintah China meluncurkan kebijakan Common Prosperity. Platform internet Douyin (semacam Tiktok lokal) diwajibkan menyensor konten yang memamerkan hedonisme. Banyak kantor mulai melarang pegawainya memakai barang mewah saat bekerja.
Bagaimana dengan Indonesia? Sampai hari ini, konten-konten crazy rich dan sultan-sultan masih merajai media sosial. Keluarga para pejabat pun tanpa malu menikmati privilesenya dan memamerkannya. Masyarakat terus dijejali dengan imajinasi semu tentang kemuliaan. Sebagiannya memaksa diri mengejarnya dengan berutang. Sebagian lagi semakin frustrasi karena jarak yang semakin jauh dengan realita mereka.
Yang menyedihkan, semua kasus korupsi yang terungkap selalu menyingkap perilaku hedon para pelakunya.
Sampai sejauh mana budaya ini akan merangsek kehidupan kita? Entahlah. Semoga tidak sampai menunggu punggung Indonesia menjadi patah.
_______________
Artikel ini dimuat pertama kali di rubrik “Udar Rasa” Kompas, 23 Juni 2024