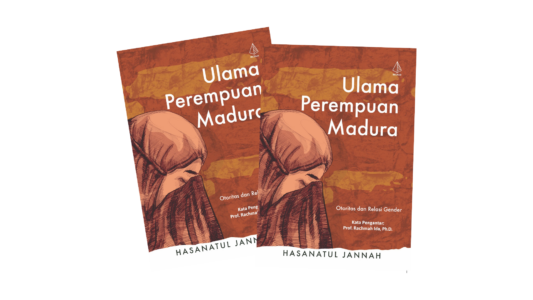Selama ini pemegang otoritas keagamaan terutama dalam Islam selalu dipegang oleh ulama laki-laki (kiai), jarang sekali yang menyoroti peran ulama perempuan (nyai), terlebih dalam masyarakat patriarkis di Madura. Namun, dalam buku Ulama Perempuan Madura yang ditulis oleh Hasanatul Jannah ini akan menunjukan pandangan yang berbeda. Buku ini merupakan pengembangan hasil riset disertasi doktoral tentang otoritas dan relasi gender nyai (ulama perempuan) di Madura.
Secara letak geografis, Madura memiliki kedekatan dengan pulau Jawa. Hal itu sedikit banyak menyebabkan struktur relasi dan keyakinan masyarakatnya dipengaruhi oleh sejarah kebudayaan Jawa, terutama kerajaan-kerajaan Islam. Meski demikian, Madura tetaplah suatu entitas masyarakat yang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan lainnya. Terutama dalam hal kultur, Madura lebih berani dalam menampilkan khazanah kebudayaannya.
Dalam konstruksi sosial-religiusitasnya, masyarakat Madura mengedepankan nilai-nilai agama di setiap sendi kehidupannya, sehingga memandang penting sosok ulama. Bagi masyarakat Madura, ulama tidak hanya dianggap sebagai tokoh pemimpin agama saja tapi juga rujukan dan panutan hampir meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ulama Madura memegang peranan sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan ekonomi.
Itu sebabnya meski berbagai program pemerintah dirancang untuk memberi manfaat kepada masyarakat, namun jika tidak ada legitimasi dari ulama, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Hal ini menunjukan posisi sentral seorang ulama bagi masyarakat Madura. Karena ulama dianggap tidak hanya sebagai subyek yang mampu mengajarkan nilai-nilai keagamaan saja, tapi juga mempunyai kekuatan berkah.
Mengingat pentingnya posisi ulama ini, lalu di mana peran ulama perempuan (nyai)? Sebagai tokoh yang tidak sentral dalam masyarakat patriarki Madura, ternyata para nyai ini mampu memainkan peran yang berhasil melakukan negosiasi kultural, sehingga mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat.
Walaupun ulama di Madura didominasi oleh ulama laki-laki (kiai) bukan berarti ulama perempuan tidak mempunyai kontribusi dalam ruang keulamaan. Hal ini dibuktikan dengan para perempuan yang terafiliasi dengan organisasi keulamaan, terutama masyarakat Madura yang secara tradisi dan konsep keislaman merupakan basis massa dari Nahdlatul Ulama (NU) sehingga banyak yang berpartisipasi dalam jaringan keulamaan berupa pertemuan publik, kegiatan keagamaan dalam wadah khusus keperempuanan seperti Fatayat dan Muslimat.
Sebenarnya banyak nyai yang memiliki peranan penting tak kalah dari kiai, bahkan mereka juga mempunyai jemaah yang besar, pengaruh yang luas, dan juga entitas tersendiri. Hanya saja, peranannya kerap kurang dilihat karena seorang nyai dianggap hanya sebagai pelengkap sang kiai. Adanya pemberlakuan pembatasan kiprah dengan menggunakan legitimasi agama, membuat mereka minim menampakkan keberanian untuk mengungkap fakta tentang dirinya sendiri, kecerdasannya sendiri dan pengikutnya (jemaah) sendiri.
Azyumardi Azra menyoroti bahwa pengetahuan tentang ulama perempuan masih sangat terbatas, gelap dan tidak mendapat tempat yang pantas dalam sumber-sumber sejarah Muslim. Hal ini terbukti dari masih minimnya literatur tentang ulama perempuan Nusantara, terutama ulama perempuan Madura. Belum banyak yang secara khusus meneliti tentang bagaimana sepak terjang dari ulama-ulama perempuan, selain dari sebagian kecil cerita yang kita temukan dalam biografi yang membahas khusus ulama laki-laki.
Biasanya, dalam sepotong cerita itu seorang nyai ditampilkan sebagai istri dan pendamping seorang kiai, yang mana aktivitas dan peranannya dipahami sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan yang sudah semestinya dilakukan oleh seorang istri sebagai pendamping suami. Sehingga para nyai tidak mempunyai sejarah mereka sendiri yang khusus merekam perjuangannya. Dalam budaya patriarki, hampir selalu peran perempuan dilekatkan dengan peran laki-laki. Artinya, adanya kontribusi perempuan tidak lepas dari peran laki-laki.
Pemahaman akan perempuan yang tidak mampu berdiri sendiri, secara tidak langsung bentuk alienasi terhadap kecerdasan perempuan yang juga mampu setara dengan laki-laki. Bahkan sejarah sudah membuktikan, peranan ulama perempuan dunia yang bisa menjadi guru spiritual bagi ulama-ulama laki-laki.
Seperti Sayyidah Nafisah, ulama perempuan yang menjadi guru Imam Syafii. Juga ada Ummu al-Fadl al-Wahatiyyah yang memiliki banyak murid laki-laki seperti Syekh Abu Sahl Muhammad bin Sulaiman, Syekh Abu al-Qasim al Razi, dan Syekh Muhammad al-Farra.
Sebenarnya, ketokohan ulama perempuan Madura bukannya tidak ada sama sekali. Sebagai contoh, ada perempuan yang dimuliakan oleh masyarakat Madura, yaitu Syarifah Ambani yang kemudian dikenal dengan sebutan Ratu Ebu. Hingga saat ini, petilasannya bahkan dikeramatkan dan sering dikunjungi oleh para peziarah. Ratu Ebu menjadi simbol kekuatan religiusitas ulama perempuan Madura yang memiliki pengaruh bagi masyarakat Madura.
Selain itu juga, menurut penelitian Huub de Jonge di Prenduan Sumenep menjelaskan, bahwa setelah kemerdekaan Indonesia, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan seperti madrasah dan pesantren yang mana awal berdiri hingga perkembangannya tidak lepas dari kiprah para nyai seperti Nyai Siddiqah, Nyai Fatmah dan Nyai Helmah. Mereka terlibat dalam kepemimpinan lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa peran nyai Madura tidak kalah krusial dalam kedudukannya di tengah anggota masyarakat.
Mereka mampu melaksanakan tanggung jawab domestik dan publik, yang mana hal itu membutuhkan keahlian untuk melakukan bargaining position dengan kiai. Karena sejatinya, peranan dan eksistensi kiai dan nyai saling menopang. Dan penting ke depannya, perlu didorong riset untuk meneliti para ulama perempuan di Nusantara. Tidak hanya nyai yang ada di Madura, tapi juga daerah lainnya untuk menambah khazanah keulamaan perempuan Nusantara.