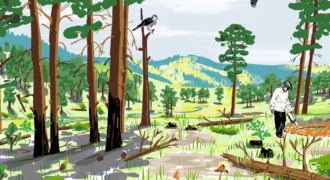YOGYAKARTA – Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta menggelar diskusi “Perspektif Keadilan Iklim” di Aula Kantor Yayasan LKiS pada hari Minggu (9/2/2025) lalu. Kegiatan ini mempertemukan jurnalis media mainstream, lembaga pers mahasiswa, serta komunitas dan aktivis pegiat lingkungan yang ada di Jogja.
Program Officer Yayasan LKiS, Moh. Ali Rohman, menyampaikan krisis iklim menjadi ancaman serius bagi penghuni bumi. Sayangnya masih banyak warga yang acuh terhadap situasi tersebut.
“Diskusi yang diselenggarakan bersama jurnalis pada hari ini merupakan langkah dalam menarasikan krisis iklim ini ke ruang publik dan sekaligus menjadi sebuah edukasi yang massif,” ujarnya.
Ia mengatakan, jurnalis sebagai satu profesi yang memberikan informasi ke ruang publik perlu menyampaikan ancaman krisis iklim yang sedang terjadi. Hal ini semata-mata sebagai langkah edukasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis iklim.
Ali menilai, jaringan jurnalis memiliki kesempatan besar untuk mengintegrasikan pengetahuan masyarakat adat ke dalam liputan, menceritakan dengan menarik dan memanfaatkan pengalaman lapangan, lalu menyeimbangkan antara menyampaikan tingkat keparahan krisis dan tindakan yang menginspirasi masyarakat luas.
Sementara itu, Koordinator Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Yogyakarta, Etik Setyaningrum menuturkan, dari tahun ke tahun, cuaca ekstrem makin sering dirasakan. Hal ini diakibatkan oleh pemanasan global atau sinyal pemanasan yang sudah terjadi termasuk di Indonesia.
“Misalnya saja di 2016, suhu bumi mencapai 1.28°C di atas suhu rata-rata massa pra-industri. Di Indonesia, anomali maksimum tercatat di Stasiun Meteorologi Sentani – Jayapura [sebesar 0.8 °C] pada tahun 2022,” paparnya.
Dijelaskan juga olehnya, perubahan iklim menyebabkan bencana hidrometeorologi yang makin sering terjadi. Bencana hidrometeorologi yakni bencana yang berhubungan dengan air dan atmosfer.
“Kebanyakan air jadi banjir, kurang air jadi kekeringan, atmosfer terlalu lembab bisa menyebabkan beberapa varietas tidak dapat panen dan lain sebagainya,” ujarnya.
Anggota Jaringan Masyarakat Peduli Iklim (Jampiklim), Heron, mengatakan faktor utama perubahan iklim adalah ulah manusia. Sektor terbesar perubahan iklim adalah sektor industri, energi fosil, gas bumi, batu bara, dan lain-lain.
“Per tiga tahun terakhir, pemberian izin eksplorasi batu bara dari pemerintah meningkat. Itu seperti tidak dilihat. Indonesia di kementerian punya Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, tapi renstra mereka tidak cukup kuat juga memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk meninjau izin yang sudah ada karena dampaknya sudah besar sekali. Izin pertambangan dan minyak tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi pemanasan global,” katanya.
Di sisi lain, Anggota AJI Yogyakarta, Abd. Mughis, mengatakan walaupun jurnalis dekat dengan persoalan tersebut, nyatanya isu krisis iklim kurang menjadi perhatian. Salah satunya disebabkan algoritma media yang lebih menekankan views hingga viralitas.
Menurutnya, keadaan tersebut diperparah dengan tuntutan kuantitas pemberitaan yang menyebabkan kualitas pemberitaannya kurang mendalam. “Tak jarang jurnalis lebih menyukai menulis berita atau informasi yang tengah viral dan dianggap seksi di meja redaksi,” katanya.
Melalui diskusi ini, diharapkan adanya kesadaran dan peran aktif jurnalis bersama masyarakat sipil dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, khususnya di DIY, melalui narasi dan edukasi perubahan iklim di ruang publik agar lebih massif.
Meneladani Jejak Perjuangan Gus Dur dalam Persoalan Lingkungan
Menyoal diskusi di atas, saya sebagai pengagum sosok Gus Dur yang terhitung baru alias newborn lantas berpikir dan teringat bagaimana Gus Dur memperjuangkan kepeduliannya terhadap lingkungan khususnya Indonesia ini. Berbekal dari beberapa bahan bacaan yang saya baca, setidaknya menukil sedikit dari pernyataan Asman Aziz Penggerak GUSDURian Samarinda Kalimantan Timur, menyebutkan ada sembilan jejak Gus Dur di dalam konteks kepeduliannya terhadap lingkungan.
Gus Dur semasa hidupnya mengupayakan agar terwujud keadilan ekologis pada semua warga. Namun, kata Asman, kepedulian Gus Dur pada isu-isu lingkungan ini belum terlalu familiar sebagaimana pemikirannya dalam konteks lintas iman dan pribumisasi Islam yang sangat populer. Padahal jejak Gus Dur yang selalu memberikan pendampingan, memperjuangkan pengelolaan dan keadilan ekologis juga sangat kuat.
Sembilan nilai itu antara lain, pertama Gus Dur sebagai pendukung sekaligus pelindung para aktivis lingkungan pada zaman Orde Baru. Salah satu tempat teraman ketika para aktivis diintimidasi rezim militer Orde Baru kala itu adalah PBNU karena ada Gus Dur yang selalu siap menjadi pendukung dan pelindung.
Kedua, Gus Dur adalah seorang penganjur reforma agraria yang sangat militan. Pada zaman Orba, melalui ceramah-ceramahnya, Gus Dur sangat lantang mengkritik soal perampasan tanah rakyat oleh negara. Menurut Gus Dur, ada 40 persen tanah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) adalah tanah yang dirampas dari rakyat dan harus dikembalikan kepada rakyat oleh negara.
Ketiga, Gus Dur mendorong lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR ini lahir pada saat Gus Dur menjadi presiden.
Keempat, Gus Dur merupakan pelopor dan inspirator pembangunan berbasis maritim. Saat menjabat Presiden, pada tahun 1999, Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut yang kini menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kelima, Gus Dur adalah pelopor lahirnya green party. Gerakan ini bukan dalam pengertian partai berwarna hijau seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan Gus Dur. Tetapi green party itu bermakna bahwa partai politik harus punya komitmen yang kuat atas keberlanjutan lingkungan dan keadilan pengelolaan ekologi.
Keenam, Gus Dur dikenal sangat getol dalam melawan industri ekstraktif. Sebab industri ekstraktif, dalam praktiknya, sangat merugikan masyarakat sekitar dan menghancurkan lingkungan. Salah satunya yang terjadi pada saat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Ketujuh, Gus Dur memiliki terobosan kebijakan moratorium logging dan hutan selama 10-20 tahun untuk keberlanjutan kelestarian ekosistem dengan diikuti restorasi, koreksi regulasi, dan kebijakan atas para perusak sumber daya alam (SDA). Ini dibuktikan Gus Dur dengan langsung memecat para menterinya yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kerusakan lingkungan.
Kedelapan, Gus Dur punya gagasan tentang membangun kurikulum pendidikan Islam berbasis lingkungan. Ini juga salah satu kritik Gus Dur terhadap paradigma sebagian besar gerakan Islam dan pemikir-pemikir Islam yang sangat developmentalisme, sehingga tidak memberikan ruang untuk penguatan pendidikan agama yang juga bermuatan lingkungan.
Kesembilan, Gus Dur dianugerahi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sebagai tokoh pejuang lingkungan pada 2010.
Berdasar jejak perjuangan inilah, mengapa ketika saya menulis saya ingat betul bagaimana peran serta pengambilan langkah tanpa ragu namun terukur, ia (Gus Dur) lakukan yang kesemuanya mengarah pada pengendalian krisis iklim.
Bersamaan hal itu, sebagai pengagum Gus Dur barang tentu menjadi praktik baik bagi diri saya sendiri untuk ikut serta mengkampanyekan gerakan cinta lingkungan, tak berhenti di situ melalui jejaring GUSDURian, khususnya jejaring yang ada di Wonosobo harus mulai melakukan aksi-aksi dan kontribusi nyata untuk lingkungan. Terlebih, Wonosobo hari ini bisa dinyatakan darurat sampah.