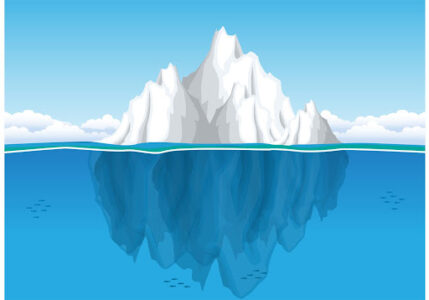Di sebuah grup jejaring sosial ramai dibahas tentang fenomena tahunan yang sudah menjadi rahasia umum bagi sebagian masyarakat Indonesia, yaitu menumpuknya kegiatan institusi-institusi pemerintah di bulan November. Undangan datang bertubi-tubi dan para pejabat pemimpinnya berlarian dari satu meeting ke meeting lainnya, sering kali hanya membuka acara tanpa sempat bekerja lebih deliberatif.
Kamar-kamar hotel mendadak sulit didapatkan karena penuh oleh berbagai acara kementerian/lembaga negara. Demikian juga ruang-ruang pertemuan. Tak ketinggalan, tiket transportasi pun habis diborong untuk para peserta kegiatan-kegiatan tersebut. Hukum ekonomi tentu berjalan: harga-harga jasa terkait menjadi melesat. Masyarakat umum pun ikut terkena dampak harga-harga ini.
Rata-rata, pegawai negeri sipil di Indonesia mengalaminya. Banyak yang bercerita bagaimana mereka hampir tidak mempunyai waktu untuk keluarga di akhir tahun akibat kesibukan keluar masuk kegiatan tersebut. Tak jarang keluarga pun diboyong ke venue acara di hotel-hotel.
Di kalangan yang terlibat, fenomena ini disebut sebagai ”Sindrom November”. Di bulan ini, lembaga negara mulai sibuk mengatasi ketertinggalan rencana kegiatan yang telah dirancang untuk tahun berlangsung. Tak kalah penting, bahkan menjadi faktor utama, adalah kebutuhan untuk segera menghabiskan anggaran yang telah tersedia untuk tahun yang bersangkutan.
Pendekatan menghabiskan anggaran ini mengikuti logika penganggaran tentang perencanaan program pemerintah. Institusi negara dipandang baik apabila anggaran terserap dan program berjalan sesuai rencana. Apabila program tidak terlaksana atau anggaran kurang terserap, catatan diberikan kepada institusi tersebut dalam penganggaran tahun berikutnya terkait kecermatan dan kapasitas organisasi. Semisal, anggaran Rp 100 miliar yang hanya terserap Rp 80 miliar tahun ini menjadi catatan yang membuat pada tahun berikutnya institusi tersebut hanya mendapatkan sebesar serapan yang ada.
Alhasil, setiap akhir tahun terjadilah gelombang penghabisan anggaran untuk mengejar serapan maksimal. Bagi para pejabat, cerita horor adalah saat mereka harus mengembalikan dana sisa anggaran kepada bendahara negara. Maka, segala cara dilakukan untuk meningkatkan penyerapan tersebut, sering kali dengan mengesampingkan capaian kualitatif sesuai dengan rencana strategis.
Fenomena ini betul-betul menggambarkan apa yang disampaikan Peter Senge, salah satu tokoh berpengaruh dalam dunia manajemen strategis. Senge dikenal dengan konsep system thinking dengan salah satu instrumennya, yaitu analisis gunung es (iceberg analysis).
Senge menggambarkan bahwa fenomena yang terlihat gamblang dalam sebuah sistem hanyalah semacam puncak gunung es yang kita lihat di atas permukaan laut. Ia ditopang oleh badan gunung es yang besar dan setidaknya dibentuk oleh tiga lapisan utama: pola, struktur sistem, dan model mental.
Lapisan pertama di bawah permukaan laut adalah tren atau pola yang terbangun dan menyebabkan makin maraknya fenomena. Dalam hal fenomena Sindrom November, di antara pola yang terjadi adalah menunda-nunda pelaksanaan kegiatan di tengah tahun serta melaksanakan kegiatan hanya untuk menghabiskan anggaran dan bukan untuk mendorong perubahan bangsa dan negara.
Lapisan pertama mengantar kepada lapisan kedua, yaitu struktur sistem yang menyebabkan pola di atas berkembang. Dalam konteks ini, dimensi sistem yang menonjol adalah sistem penganggaran yang berorientasi serapan anggaran, perencanaan kegiatan yang lebih berorientasi output kegiatan dan tidak berorientasi pada outcome berupa dampak pada masyarakat, dan dimensi pejabat yang terjebak dalam birokrasi dan tidak memiliki visi transformasi bangsa.
Lapisan terdalam adalah model mental atau lebih biasa kita kenal dengan istilah mindset, dalam hal ini mindset para pelaku sistem yang menyebabkan struktur sistem yang terbentuk.
Mindset utama para birokrat dalam hal ini adalah yang penting anggaran terserap demi mengamankan anggaran tahun depan. Mindset kedua adalah indikator kinerja ditentukan oleh serapan anggaran. Mindset berikutnya adalah yang bisa dikendalikan hanyalah output kegiatan. Mindset lain yang cukup dominan adalah sebagai birokrat (papan tengah) tidak perlu muluk-muluk berpikir soal perubahan masyarakat.
Peter Senge mengatakan bahwa semakin dalam kita menyelami sebuah sistem, semakin besar daya ungkit yang dapat kita temukan untuk mendorong transformasi sistem tersebut. Sebaliknya, hanya bekerja pada lapisan puncak gunung es dan lapisan pertama biasanya tidak efektif untuk mendorong perubahan berkelanjutan atau menetap.
Apabila kita bersikap reaktif pada fenomena dan pola yang muncul, kita cenderung akan mencari quick fix alias solusi sepintas. Mengebut kegiatan di akhir tahun merupakan solusi cepat atas serapan anggaran yang rendah, tetapi ia tidak menyelesaikan persoalan sistemiknya.
Serapan anggaran sebagai indikator keberhasilan kerja sejatinya merupakan upaya perubahan sistem yang tidak akuntabel. Diharapkan, dengan logika penganggaran sedemikian, para birokrat akan terpacu untuk merealisasikan kegiatan dengan lebih baik. Apa daya, ini tidak cukup.
Perubahan sistem berupa regulasi dan kebijakan serta kerangka kerja program akan sulit apabila tidak diikuti perubahan mental set para pelakunya. Konsekuensi yang terjadi adalah munculnya problem baru karena orang yang sama dengan mental set yang sama masih menghidupi sistem tersebut.
Begitulah, selama model mental para birokrat terkait serapan anggaran tidak diubah dengan sengaja dan sistematis, maka selama itu pula kita akan melestarikan Sindrom November. Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan program berkualitas, plus uang pajaknya dihabiskan untuk membiayai festival Sindrom November. Apes.
(Artikel ini dimuat pertama kali di rubrik “Udar Rasa” Kompas, 28 November 2021)
Sumber: kompas.id